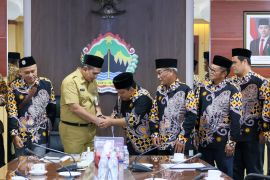"Kidung Anjampiani" merawat ingatan waras

Magelang (ANTARA) - Selepas tiga dasawarsa terhitung mulai dari perjumpaan di Kampus Mrican, sekelompok alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berkumpul, reuni lagi, namun kali itu dalam kemasan tak ingin sekadar seremonial kangen-kangenan.
Mereka iuran tulisan untuk membuat buku yang kemudian diberi judul "Kami Bawa Sadhar". Buku diterbitkan TriBEE, penerbit indi di Magelang, Jawa Tengah. Sebanyak 25 di antara para alumnus, secara bebas menulis kisah masing-masing berpijak pada pemaknaan pendidikan dan perkuliahan di kampus yang 20 Oktober nanti berusia 67 tahun.
Langgam penulisannya bebas, antara lain berupa narasi dan tutur, puisi, dan cerita pendek dengan selipan-selipan makna di sana-sini. Isinya juga macam-macam, seperti jerih payah kuliah, dosen favorit, indekos dan warung makan, profesi guru, percintaan, kuliah sambil bekerja, pentas seni kampus, perjumpaan antarbudaya, dan ada juga yang bercerita tentang karakteristik kawan-kawannya. Seorang di antara mereka menulis karyanya secara khusus dalam rupa lagu. Judulnya "Kami Bawa Sadhar".
Selain menyampaikan kritik konstruktif atas remeh-temeh isi buku 144 halaman diluncurkan pada 28 Desember 2018 saat reuni itu, budayawan yang juga pengajar Universitas Sanata Dharma (Sadhar) Romo G. Budi Subanar, juga mengemukakan keyakinannya bahwa alumnus memiliki pengalaman lebih kaya dan pemaknaan lebih mendalam atas jalan kehidupan masing-masing daripada yang tertuang di "Kami Bawa Sadhar".
Bagaimanapun juga, buku itu sudah memiliki arti dan peran penting alumnus Program Pendidikan Sejarah Sadhar tersebut dalam merawat ingatan bersama atas jalan kehidupan.
Kebiasaan dan kefasihan menulis memang terasa masih menjadi kelemahan bangsa ini, meskipun cukup banyak ragam bukti kesejarahan dalam wujud tulisan, seperti babad, serat, kidung, guritan, dan prasasti diwariskan para pujangga, pahlawan, pendiri bangsa, dan sosok-sosok legendaris lainnya pada masa lalu negeri ini.
Mungkin tak ada yang menyangka, jika dalam tahun-tahun berikutnya satu di antara mereka dalam "Kami Bawa Sadhar" seperti beroleh pemantik untuk membuat catatan-catatan perjalanan kesejarahan personal selanjutnya, menjadi penulis buku.
Hingga empat tahun setelah peluncuran buku itu, seseorang di antara mereka bernama Fransiska Sulistya Rini, guru SMA swasta di Tangerang, ternyata telah membuat 10 buku kumpulan tulisan bersama komunitasnya.
Salah satu karya terbarunya berjudul "Paket Nasi Bertabur Kasih Ibu" dalam buku terbitan CV Elfa Mediatama Cikarang Baru, Jawa Barat pada Februari 2022, berjudul "Tangan-Tangan yang Berbagi", berkisah tentang Boman, penyandang disabilitas mental, tetangganya di kampung halaman di Godean, Yogyakarta barat.
Pesan yang hendak ditaburkan penulis tentang nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan edukatif. Ia bercerita pengalaman riil nilai sanak-kadang yang masih lestari dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bawah saat ini. Dalam kisah itu, penulis seakan hendak merawat masa depan suatu nilai yang diwariskan leluhur bangsa ini.
Menuliskan sejarah
"Oh, sejarah. Segala sesuatu telah dituliskan seseorang, tapi belum semua orang menuliskan sesuatu. Rakyat di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, harus menuliskan sejarahnya sendiri," begitu Jais Darga yang berperan sebagai Martaraga meluncurkan seruan saat puncak pementasan fragmen, performa, dan ritual "Kidung Anjampiani".
Pementasan tersebut menandai peluncuran novel berjudul "Kidung Anjampiani", karya terbaru penulis Bre Redana di panggung terbuka Studio Mendut Kabupaten Magelang, Jumat (29/7) malam. Acara juga ditandai dengan diskusi dengan narasumber Guru Besar Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Anggota DPR Hendrawan Supratikno, penulis Bre Redana, dan budayawan utama Komunitas Lima Gunung Sutanto Mendut.
Di antara tawaran berbagai pihak dan sejumlah agenda seni-budaya, Bre Redana memutuskan menggelar peluncuran novelnya yang berlatar belakang sejarah Kerajaan Majapahit itu bersama para seniman petani Komunitas Lima Gunung Kabupaten Magelang dengan waktu yang dianggap keramat karena bertepatan dengan malam 1 Sura (Kalender Jawa) tahun ini.
Baca juga: Komunitas Lima Gunung luncurkan konten "Terminal Mendut"
Kali ini, sebagai peristiwa kedua Bre meluncurkan novelnya bersama Komunitas Lima Gunung setelah pada November 2020 di tengah pandemi COVID-19, ia melakukan hal serupa untuk novel "Dia Gayatri" yang juga berlatar belakang Kerajaan Majapahit.
Ketika itu, acara dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk jumlah orang secara terbatas, peluncuran novelnya pagi hari, sekitar pukul 06.00 WIB, di Candi Pendem dengan latar belakang puncak Gunung Merapi yang status aktivitas vulakaniknya baru saja naik dari level dua ke tiga (Waspada ke Siaga). Di tengah acara, satu Maja jatuh dari pohonnya di dekat batu candi. Buah Maja dalam catatan sejarah menjadi cikal bakal nama kerajaan, Majapahit.
Dalam "Kidung Anjampiani", penulis juga menyusun skrip fragmen itu, sekaligus sutradara pementasan hingga menjelang tengah malam. Penonton yang hadir tidak saja dari Magelang --termasuk Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang-- tetapi juga meriung saat "malam keramat" 1 Sura, mereka dari sejumlah kota besar.
Melalui pementasan itu, seniman petani Komunitas Lima Gunung mentranformasi tarian rakyat yang populer dari kawasan Gunung Merbabu dan Andong, "Soreng", dari berbasis cerita Kesultanan Demak (Abad 15) menjadi berbasis sejarah Kerajaan Majapahit (Abad 13-15).
Tari "Soreng" yang dikenal bercerita peperangan era Demak, antara pasukan Arya Penangsang (Jipang) menghadapi prajurit Hadi Wijaya (Pajang), diolah ulang oleh komunitas menjadi perang era Majapahit, antara Ranggalawe melawan Nambi.
Belum lama ini, sekelompok bidan Kabupaten Magelang didampingi seniman Komunitas Lima Gunung, Handoko, mengolahbarukan gerakan tarian itu untuk kepentingan kampanye enam langkah cuci tangan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, menjadi karya "Soreng Cingan". Cingan kependekan dari "cuci tangan".
Novel "Kidung Anjampiani" yang diakui penulisnya melalui riset terhadap berbagai sumber penting dan utama sejarah Majapahit dan perjalanannya ke berbagai tempat di kawasan yang masa lalu sebagai kerajaan itu, kentara bercerita tentang percintaan pujangga muda Kuda Anjampiani (anak Ranggalawe-Martaraga) dan Dewi Sekartaji Anjasmara (dikisahkan penulis sebagai anak bungsu Nambi).
Karya itu juga bercerita penggalan penting persoalan politik kerajaan dan sejarah yang perspektif. Novel itu, terkesan pula meruntuhkan stigma pemberontak atas diri Ranggalawe dan kebijakan Nambi menyikapi kecenderungan arus politik kekuasaan pada masanya setelah Raja Kertanagara Jayawardana (Raden Wijaya) mangkat digantikan Raja Jayawardana (Kala Gemet).
Sumber sejarah mencatat Nambi kalah perang melawan Ranggalawe, tetapi melalui perwira Lembu Anabrang membunuh adipati Tuban itu, salah satu wilayah Kerajaan Majapahit, di Sungai Tambak Beras.
Bre menghadirkan getaran naluri purba manusia dalam wajah asmara Anjampiani-Dewi Sekartaji dalam novelnya, yang oleh Hendrawan Supratikno --kawan penulis sejak masa aktif mereka di pers kampus Universitas Satyawacana Salatiga-- dipandang membantu pembaca ikut merawat kewarasan, pencerahan, dan kebudayaan.
Tak dimungkiri dalam "Kidung Anjampiani" juga hadir catatan ingatan atas jalan kehidupan personal penulisnya, termasuk tentu saja macam ragam seruakan pesan makna, moral, wawasan, kecerdasan, dan kearifan.
Terlebih menyangkut pencerahan atas nilai sejarah masa lalu yang mengantar Anjampiani-Dewi Sekartaji menuliskan sendiri kesejarahannya.
"Kidung Anjampiani" seakan hendak membawa konfirmasi peran penting hakikat naluri purba dalam merawat setiap orang untuk waras menuliskan sejarahnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: "Kidung Anjampiani" merawat ingatan waras
Oleh M. Hari Atmoko
Editor:
Wisnu Adhi Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2026